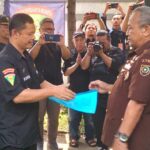Porosmedia.com | Tasikmalaya – PAJNADAYN, PALESTIN – Debu gurun membayangi langit siang, membuat mata pedih dan nafas sesak. Di tengah hamparan tanah kering yang membara itu, pada tahun 634 Masehi, suatu pertempuran dahsyat berkecamuk. Pasukan Muslimin yang berjumlah jauh lebih kecil, tercengang. Barisan mereka mulai goyah dihantam oleh gelombang demi gelombang legiun Rom Byzantine yang lengkap bersenjata dan berpengalaman. Banyak sahabat telah gugur. Harapan seakan menyusut bersama terbenamnya mentari.
Tiba-tiba, dari balik kepulan debu dan kekacauan, sebuah siluet muncul bagai bayangan yang hidup. Seorang penunggang kuda, seluruh tubuhnya dibalut jubah dan pakaian hitam legam, dari ujung rambut hingga kaki. Hanya sepasang mata tajam yang menatap dari balik kain penutupnya. Tanpa seruan komando, tanpa gertak teriakan, pahlawan misterius ini melesat bagai anak panah, menyerbu jantung pertahanan musuh seorang diri.
Aksinya liar, lincah, dan mematikan. Sebuah tombak di tangan kanan, sebilah pedang di tangan kiri. Setiap sabetan dan tusukan adalah penghabisan. Dua, tiga, kepala prajurit Rom berguling di tanah. Dia menyusup ke tengah lautan musuh bagai serigala masuk ke kandang domba, mencipta pusaran kepanikan di tengah barisan yang rapi. Mereka belum pernah melihat gaya bertarung begitu nekad, begitu mahir, dan begitu penuh amuk.
Dari atas bukit, Panglima Besar Khalid bin Al-Walid—sang “Pedang Allah yang Terhunus”—hanya mampu memandang dengan mata terbelalak. Sang legenda hidup itu sendiri terpana. Dalam benaknya, ini pastilah bala bantuan yang datang tak terduga. Kekaguman itu memuncak hingga ia berbisik, “Andai aku tahu siapa pahlawan ini, niscaya akan kuangkat ia sebagai pemimpin sayap serangan!”
Keberanian pahlawan hitam itu bagai percikan api di ladang gersang. Semangat pasukan Muslim yang nyaris padam, membara kembali. Mereka bangkit, menyusul, dan menyerang balik dengan kekuatan baru. Momentum perang pun berbalik. Kekalahan yang hampir pasti, berubah menjadi kemenangan gemilang.
Darah, Debu, dan Sebuah Rahasia
Saat pertempuran usai, pahlawan misterius itu berdiri sendiri. Jubah hitamnya kini basah kuyup, diwarnai bukan oleh keringat, tetapi oleh darah musuh yang masih hangat. Khalid Al-Walid dan para prajurit segera mengepungnya, penasaran dan penuh hormat. Siapa gerangan penyelamat di saat genting itu?
“Wahai pahlawan,” kata Khalid dengan suara tegas penuh wibawa, “Bukalah penutup wajahmu. Kami ingin mengenalimu.”
Sang pahlawan diam, memalingkan muka, segan dan enggan. Namun desakan Khalid dan kerinduan seluruh pasukan untuk memberi penghargaan tak terbendung. Akhirnya, dengan gemetar, pahlawan itu mengangkat tangan dan membuka ikatan penutup wajahnya.
Gasps keheranan terdengar bersahutan. Di balik pakaian perang yang garang, tersembul wajah yang lembut dan halus. Suara yang keluar kemudian bukanlah bass berat seorang jagoan, melainkan suara lembut seorang wanita.
“Khawlah,” perkenalnya lirih, “Khawlah binti Al-Azwar.”
Dialah saudari kandung dari panglima Derar bin Al-Azwar, seorang prajurit tangguh yang ditangkap musuh dalam pertempuran sebelumnya. Air mata mulai menggenang di matanya saat ia menjelaskan, “Hatiku tak tahan hanya duduk di kemah, wahai Panglima, sementara kakakku menjadi tawanan. Aku memilih untuk bertarung. Lebih baik aku mati syahid daripada hidup dalam kecemasan tanpa berusaha menyelamatkannya.”
Khalid Al-Walid terdiam. Di hadapannya bukan lagi sekadar prajurit misterius, tetapi manifestasi dari cinta saudara yang membara, yang sanggup mengubah seorang wanita lembut menjadi singa padang pasir yang paling ditakuti. Bukannya marah, Sang Panglima justru memberikan izin dan kepercayaan. Khawlah bahkan diberi tempat dalam pasukan khusus penyelamatan yang akhirnya berhasil membebaskan Derar dari cengkeraman Bizantium.
Warisan Khawlah, Antara Sejarah dan Inspirasi
Kisah heroik Khawlah binti Al-Azwar ini masyhur diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah klasik seperti “Futuh al-Sham” (Penaklukan Syam), karya Al-Waqidi dan Al-Azdi. Walaupun terdapat diskusi akademis di kalangan sejarawan modern mengenai akurasi detail naratif dan kekuatan sanad-nya—sebagaimana umumnya kajian sejarah awal Islam—kisah ini telah mengkristal menjadi bagian tak terpisahkan dari epik kepahlawanan (Sirah) Islam.
Ia bukan sekadar catatan perang, melainkan sumber ‘Ibrah’ (pelajaran dan inspirasi) yang abadi tentang semangat, keberanian, dan kapasitas perempuan dalam peradaban Islam. Dalam berbagai referensi daring seperti IslamicFinder, MuslimahActivity, dan The Muslim Vibe, nama Khawlah selalu disebut dalam daftar perempuan paling berpengaruh dan pemberani di era awal Islam.
Kisahnya adalah sanggahan telak terhadap stereotip kuno yang menggambarkan perempuan Muslim sebagai makhluk pasif dan tertindas. Khawlah membuktikan bahwa dalam tradisi Islam, perempuan bukan sekadar “hiasan di dapur”. Mereka adalah srikandi yang, ketika keadaan memanggil, tangan yang biasa menghayun buaian mampu dengan sama tangguhnya mengayun pedang membela kehormatan, keluarga, dan keyakinan.
Dia adalah pengingat bahwa terkadang, pahlawan terbesar tidak datang dengan nama dan gender yang diharapkan. Kadang, mereka datang dari tempat yang tak terduga: dari balik kemah, dari dorongan hati seorang saudari, dan dari tekad yang lebih keras daripada baja—diselimuti debu dan jubah hitam, mengubah jalannya sejarah di padang pasir Ajnadayn.