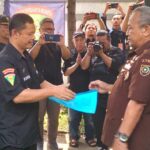Tasikmalaya | MADINAH – Suasana tenang di Masjid Nabawi suatu siang tiba-tiba retak oleh langkah mantap seorang lelaki. Dengan jubah berdebu dan aura keras khas pedalaman, ia memasuki lingkaran majelis dengan pandangan menelusuri setiap wajah. Lalu, tanpa pendahuluan, sebuah pertanyaan meluncur, lugas dan menohok: “Manakah di antara kalian yang bernama Muhammad?”
Bukan panggilan “Ya Rasulullah”, bukan juga “Wahai Nabi”. Hanya “Muhammad”, nama biasa, seperti memanggil kawannya sendiri di padang pasir. Sosok itu adalah Dhimam bin Tsa’labah, seorang Badui dari Bani Sa’d bin Bakr yang menempuh perjalanan panjang dengan untanya. Ia datang bukan untuk basa-basi diplomatik, melainkan untuk sebuah misi tunggal: verifikasi.
Bayangkan adegan itu dalam konteks modern. Seorang “outsider” dari daerah terpencil, dengan penampilan sederhana dan tutur kata tanpa filter, mendatangi pusat otoritas spiritual dan politik tertinggi—bukan istana, tetapi masjid tempat Nabi dan para pemimpin komunitas berkumpul. Ia bertanya langsung, nyaris tanpa etiket. Anas bin Malik, saksi mata peristiwa yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari, menggambarkan betapa para sahabat sempat tersentak dengan sikapnya yang dianggap kurang ajar.
Para sahabat menunjuk, “Itu orangnya. Lelaki berkulit putih yang sedang bersandar.” Dhimam langsung menyambarnya, “Wahai Ibnu Abdul Muththalib?” Nabi menjawab tenang, “Aku mendengarmu.” Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari mencatat, Nabi sengaja tidak menjawab “iya” yang biasa digunakan orang Arab. Ini adalah isyarat halus untuk mendidik adab, mengingat firman Allah dalam QS. An-Nur: 63 yang melarang memanggil Rasul seperti memanggil sesama manusia biasa.
Namun, Nabi ﷺ tidak menghardik. Ada sesuatu dalam keteguhan dan ketulusan Dhimam yang terbaca. Sebelum bertanya, Dhimam bahkan sempat “berunding”, “Aku akan bertanya sesuatu yang mungkin membuatmu tidak berkenan. Maka janganlah engkau menyimpan kemarahan kepadaku.” Prof. Dr. Ali Muhammad ash-Shallabi, dalam bukunya Sirah Nabawiyah, menjelaskan bahwa sikap Nabi ini mencerminkan prinsip utama dakwah: kelembutan (al-hilm) terhadap pencari kebenaran, meskipun cara mereka belum sempurna.
Di sinilah dialog bersejarah itu bergulir, sebuah tanya-jawab yang menurut Umar bin Khattab (seperti diriwayatkan Abu Hurairah) adalah yang “paling baik, paling ringkas, dan paling jelas” yang pernah ia saksikan.
Dhimam bertanya dengan sumpah demi Rabb langit dan bumi:
- “Apakah benar Allah mengutusmu kepada seluruh manusia?”
- “Apakah Allah memerintahkan shalat lima waktu, puasa Ramadhan, dan zakat?”
Jawaban Nabi singkat, tegas, dan diakhiri dengan “Ya Allah, benar.”
Tidak ada debat kusir. Tidak ada negosiasi. Hanya klarifikasi atas hal-hal paling fundamental. Setelah itu, Dhimam langsung menyatakan, “Aku beriman kepada semua yang engkau bawa.”
Dalam sekejap, ia berubah dari pencari (seeker) menjadi pembawa cahaya (light-bearer). Ia pulang bukan dengan tangan hampa, tetapi sebagai duta pertama bagi sukunya. Dr. Musthafa Dieb al-Bugha dalam Al-Wafi menyebutkan bahwa Dhimam kembali kepada kaumnya dan semua orang dari Bani Sa’d bin Bakr pun masuk Islam berkat dialog singkat dan kejujurannya. Ini menunjukkan kekuatan komunikasi yang transparan dan berbasis keyakinan personal.
Kisah Dhimam seringkali hanya dibaca sebagai contoh adab yang “dimaafkan” karena ketidaktahuan. Padahal, esensinya jauh lebih dalam. Ia adalah ikon integritas intelektual dan keberanian verifikasi. Sebagaimana diulas dalam portal kajian Islam seperti Islamweb.net, Dhimam telah sampai pada kesimpulan rasional tentang Tuhan. Yang ia butuhkan hanyalah konfirmasi tentang kebenaran utusan-Nya. Ketika ia mendapati jawaban yang jelas dan selaras dengan reputasi Nabi sebagai al-Amin (yang terpercaya), iman langsung mengkristal tanpa keraguan.
Ini adalah model keislaman yang unik. Berbeda dengan banyak sahabat yang terdorong oleh faktor sosial, politik, atau keadilan ekonomi, jalan Dhimam murni intelektual-spiritual. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan latar belakang tidak identik dengan kedangkalan berpikir. Seorang Badui dari pelosok justru datang dengan pertanyaan-pertanyaan esensial yang menggetarkan pusat peradaban baru.
Di era banjir informasi dan klaim kebenaran hari ini, kisah Dhimam bin Tsa’labah mengingatkan kita pada nilai keberanian bertanya, kejernihan bernalar, dan ketulusan menerima kebenaran di mana pun ia ditemukan. Ia mengajarkan bahwa pintu iman terbuka lebar bagi setiap pencari yang jujur, meski ia datang dengan bahasa yang masih berdebu dari perjalanan.
Dan, pada akhirnya, cahaya itu sering kali datang dari arah yang paling tak terduga.
Sumber Referensi Tambahan:
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. Sirah Nabawiyah. (Untuk analisis sikap Nabi ﷺ).
- Al-Bugha, Musthafa Dieb. Al-Wafi Syarh Arba’in an-Nawawi. (Untuk dampak dakwah Dhimam kepada kaumnya).
- Islamweb.net. Articles on the Story of Dhimam bin Tha’labah. (Untuk tafsir kontemporer tentang aspek intelektual kisah ini).
- Shahih Bukhari, Kitab Al-Ilm. (Hadis utama riwayat Anas bin Malik).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. (Untuk penjelasan linguistik dan adab dalam dialog).
- Hukum Pidana Kumpul Kebo 2026 Mulai BerlakuJAKARTA, Porosdaerah – Pasangan yang menjalani hidup bersama tanpa ikatan perkawinan resmi, atau yang kerap disebut “kumpul kebo” (cohabitation), harus bersiap menghadapi ancaman sanksi hukum pidana mulai 2 Januari… Baca Selengkapnya: Hukum Pidana Kumpul Kebo 2026 Mulai Berlaku
- IWS dan LVRI Perkuat Jejaring, Bahas Peran Veteran dalam Pendidikan Karakter BangsaPorosmedia.com | Jakarta, 1 Januari 2026 – Dalam sebuah pertemuan strategis, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Warga Satya Indonesia (IWS) melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Legiun… Baca Selengkapnya: IWS dan LVRI Perkuat Jejaring, Bahas Peran Veteran dalam Pendidikan Karakter Bangsa
- Patroli Intensif Polres Tasikmalaya Kota Siagakan Malam Tahun Baru, Kawal Kamtibmas dan Tekan PekatTasikmalaya, 1 Januari 2026 – Menjelang perayaan pergantian tahun, jajaran Polres Tasikmalaya Kota menggenjot intensitas patroli di berbagai titik rawan. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif untuk… Baca Selengkapnya: Patroli Intensif Polres Tasikmalaya Kota Siagakan Malam Tahun Baru, Kawal Kamtibmas dan Tekan Pekat
- Ketika Sedekah Kembali Berbuah Tak TerdugaSuasana masjid di Madinah sepulang shalat jamaah terasa tenang. Nabi Muhammad SAW duduk bersila dikelilingi para sahabat, membahas urusan umat. Ketenangan itu tiba-tiba terbelah oleh langkah… Baca Selengkapnya: Ketika Sedekah Kembali Berbuah Tak Terduga
- Dari Badui yang “Kasar” hingga Jadi Pembawa CahayaTasikmalaya | MADINAH – Suasana tenang di Masjid Nabawi suatu siang tiba-tiba retak oleh langkah mantap seorang lelaki. Dengan jubah berdebu dan aura keras khas pedalaman,… Baca Selengkapnya: Dari Badui yang “Kasar” hingga Jadi Pembawa Cahaya